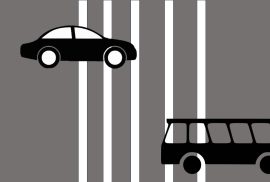JUARA I: Critical Review Modernisasi Pelabuhan dalam Konteks Dekarbonisasi
dan Ekonomi Sirkular
Oleh: Arrida Hamzah
Tulisan ini berfokus pada analisis terhadap edisi buku “Perspektif Kebijakan Pengembangan Pelabuhan di Indonesia”. Catatan terhadap buku ini di antaranya mengenai upaya keberlanjutan, ESG compliance, dan green financing. Catatan terkait hal ini setidaknya dibahas dalam salah satu chapter buku ini, yakni chapter 7 (dekarbonisasi dan ekonomi sirkular). Chapter ini mengupas dua isu sentral: dekarbonisasi, yaitu upaya pengurangan jejak karbon melalui teknologi dan pemanfaatan energi terbarukan atau ekonomi sirkular yang berfokus pada pengelolaan limbah dan optimalisasi penggunaan kembali sumber daya.
Dalam bab ini, penulis menunjukkan bahwa inovasi teknis harus bersamaan dengan perubahan paradigma pengelolaan. Hal ini setidaknya ditunjukkan pada tiga poin utama, yakni: pertama, pendekatan sirkular, di mana dipaparkan sebagai peluang bagi operator pelabuhan untuk meminimalkan limbah sehingga berdampak positif pada efisiensi biaya, misalnya dengan memanfaatkan kembali scrap metal atau sisa bahan bakar kapal. Terdapat pula solusi teknis seperti cold ironing, yakni penyediaan listrik darat untuk kapal guna mengurangi emisi. Kedua, pentingnya skema pembiayaan hijau, penulis menekankan peran instrumen pembiayaan seperti green bonds dan skema KPBU sebagai mekanisme pendanaan strategis untuk mendukung investasi teknologi rendah karbon. Hal ini semakin relevan mengingat perkembangan Green Sukuk Indonesia yang telah berhasil mengumpulkan dana signifikan (OJK, 2023). Ketiga, kesesuaian dengan kebijakan, di mana policy framework yang diusulkan relevan dengan target nasional Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 (NDC Indonesia, 2022).
Bab ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut: pertama, chapter ini kurang menyertakan analisis biaya-manfaat (cost- benefit analysis) yang mendalam. Hal ini menyulitkan investor dan pembuat kebijakan untuk menilai kelayakan serta dampak ekonomis dari penerapan teknologi tersebut. Kedua, beberapa tantangan utama belum diuraikan secara mendalam. Chapter ini menyoroti skema KPBU dan green bonds sebagai instrumen pendanaan, namun peluang dan tantangannya belum dianalisis secara komprehensif. Semisal Green Sukuk Indonesia telah mengumpulkan USD 6,9 miliar selama 2018-2023, namun hanya 15% dialokasikan untuk sektor transportasi (OJK, 2023). Terdapat pula regulasi yang tumpang tindih, seperti Perpres No. 109/2023 tentang proyek strategis nasional yang belum mengikat target dekarbonisasi pelabuhan secara spesifik. Ketiga, chapter ini juga belum menyediakan peta jalan komprehensif untuk mewujudkan kolaborasi lintas sektor yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan limbah dan penggunaan kembali sumber daya secara efektif.
Literatur yang membahas terkait kepelabuhanan dari aspek kebijakan masih begitu minim. Jika dibandingkan dengan beberapa literatur internasional, seperti buku Port Economics, Management, and Policy atau artikel di Maritime Policy & Management dan Port of Rotterdam, chapter ini kurang menyertakan studi kasus empiris yang komprehensif. Misalnya, pelabuhan-pelabuhan di Rotterdam dan Singapura telah menunjukkan implementasi nyata konsep green port dan ekonomi sirkular melalui fasilitas pengolahan limbah dan integrasi digital.
Buku ini membuka wacana dekarbonisasi pelabuhan yang masih minim di Indonesia serta memberikan kontribusi signifikan dalam menyusun visi pelabuhan berkelanjutan melalui dekarbonisasi dan ekonomi sirkular. Namun, untuk menjadikan usulan ini lebih aplikatif, diperlukan penambahan studi kasus lokal, cost-benefit analysis yang mendalam, dan peta jalan kolaboratif lintas sektor. Upaya ini diperlukan untuk mewujudkan pelabuhan Indonesia dengan visi berkelanjutan yang sejati.
Referensi
International Maritime Organization. (2021). Maritime environment: Greenhouse gas emissions from ships. International Maritime Organization
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). Laporan Dekarbonisasi Sektor Transportasi. Jakarta: Kemenhub.
NDC Indonesia. (2022). Nationally Determined Contributions to the Paris Agreement. Jakarta: Government of Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Green Sukuk Indonesia. Jakarta: OJK.
Port of Rotterdam. (2023). Sustainability in Port Operations: Cold Ironing and Emissions Reduction. Rotterdam: Port of Rotterdam Authority.
JUARA II: CRITICAL REVIEW Buku Perspektif Kebijakan Pengembangan Pelabuhan di Indonesia Penulis : Raja O.S Gurning, dkk. Penerbit : Buku Kompas Tahun Terbit 2024;Jumlah Halaman : xxxiii + 264 halaman ISBN : 978-623-523-368-0
Oleh: Donnie Trisfian
Bagaimana masa depan pelabuhan Indonesia di era digital dan keberlanjutan? Buku Perspektif Kebijakan Pengembangan Pelabuhan di Indonesia bagian dari seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia mengupas tuntas strategi dan kebijakan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut. Buku ini membahas berbagai aspek strategis, termasuk rantai pasok global, kinerja pelabuhan, dampak ekonomi regional, tata kelola, serta kebijakan pendanaan yang selaras dengan RPJPN dan RPJMN. Dua isu utama yang diangkat adalah transformasi digital dan keberlanjutan, termasuk smart port, big data, blockchain, dan green logistics. Buku ini juga menyoroti strategi pembiayaan seperti skema KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur maritim.
Buku ini memiliki cakupan luas dan relevan dengan tantangan global serta nasional. Pembahasannya mencakup ketahanan rantai pasok, deregulasi investasi, dan daya saing pelabuhan Indonesia dalam persaingan internasional. Kajian berbasis data dan studi kasus memperkuat analisis kebijakan, termasuk indeks kinerja pelabuhan yang mengacu pada standar global. Analisis peran pelabuhan pengumpan dalam pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi nilai tambah, karena menunjukkan bagaimana infrastruktur maritim dapat mendorong pembangunan yang lebih merata.
Namun, buku ini memiliki beberapa kekurangan. Pembahasan mengenai implementasi teknologi baru, seperti digitalisasi, smart port, dan blockchain, kurang mendalam, terutama dalam hal tantangan serta solusi penerapannya di Indonesia. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah berjalan juga belum tergambar jelas, sehingga dampak nyata dari regulasi sebelumnya sulit diukur. Perspektif pemangku kepentingan lokal, seperti operator pelabuhan dan pengguna jasa, masih minim karena pendekatannya lebih bersifat makro. Isu keamanan siber dalam digitalisasi pelabuhan hanya disinggung secara terbatas. Selain itu, beberapa gambar dan tabel kurang jelas, mengurangi efektivitas penyampaian data dan informasi.
Buku ini memiliki cakupan nasional yang lebih spesifik dibandingkan dengan buku Port Economics, Management and Policy yang membahas pengelolaan pelabuhan dari perspektif global. Buku tersebut menggunakan pendekatan multidisipliner dengan membahas ekonomi, geografi, manajemen, dan teknik pelabuhan secara luas. Sementara itu, buku Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan: Investasi Swasta dan Peningkatan Daya Saing lebih fokus pada investasi dan keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia, dengan penekanan pada model kerja sama pemerintah-swasta (PPP/KPBU). Dibandingkan dengan kedua buku ini, Perspektif Kebijakan Pengembangan Pelabuhan di Indonesia lebih menitikberatkan pada strategi kebijakan nasional dalam konteks modernisasi dan keberlanjutan.
Buku ini memberikan wawasan komprehensif mengenai pengembangan pelabuhan dalam konteks kebijakan nasional. Pembahasannya yang luas dan berbasis data menjadikannya sumber rujukan penting bagi akademisi dan praktisi di bidang maritim. Namun, agar lebih aplikatif bagi berbagai kalangan, buku ini dapat diperkaya dengan memperdalam mengenai implementasi teknologi baru dan evaluasi kebijakan yang telah berjalan. Selain itu, penambahan kajian mengenai pelabuhan kecil dan daerah terpencil akan meningkatkan relevansi buku ini dalam konteks pembangunan maritim yang inklusif. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi referensi yang lebih lengkap dan relevan bagi pengembangan pelabuhan di Indonesia.
Referensi:
Notteboom, T. dkk (2022). Port Economics, Management and Policy. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429318184
Hariyadi, dkk. (2020). Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan: Investasi Swasta dan Peningkatan Daya Saing. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
JUARA III: Critical review terhadap bab buku “Telaah Sistem dan Tata Kelola Kepelabuhan di Indonesia Serta Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Pelabuhan Komersial” yang ditulis oleh Wihana Kirana Jaya & Hengki Purwoto
Oleh: Chairul Fajar
Pendahuluan
Melalui Bab buku ini, penulis berupaya mengurai sistem dan tata kelola kepelabuhanan di Indonesia dengan menyoroti keragaman karakteristik pelabuhan di Indonesia, dari pelabuhan besar dengan fasilitas lengkap hingga pelabuhan kecil dengan keterbatasan sumber daya. Penulis juga berupaya melakukan analisis terkait peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
Secara keseluruhan, tulisan ini adalah upaya penulis untuk memberikan pembaca gambaran terkait bagaimana tata kelola pelabuhan di Indonesia saat ini serta bagaimana pengelolaannya berlangsung. Penulis juga memberikan rekomendasi untuk mencapai pengelolaan yang optimal. Dengan membaca bab ini, kita sebagai pembaca akan memiliki gambaran tentang bagaimana seharusnya sebuah pelabuhan dikelola dan bagaimana seharusnya pemangku kepentingan berperan dalam pengelolaannya.
Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan utama bab ini menurut saya adalah kemampuan penulis menyajikan informasi yang kompleks dengan bahasa yang relatif mudah dipahami. Saya sebagai awam yang tidak bersinggungan langsung dengan topik kepelabuhan merasa dapat memahami teks dengan mudah. Selain itu, penulis juga berhasil mengaitkan konsep-konsep teoritis seperti New Institutional Economics dengan kondisi riil kepelabuhanan di Indonesia.
Namun, bab ini menurut saya juga memiliki beberapa kekurangan. Meskipun penulis menyebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelabuhan, pembahasan mengenai solusi atau rekomendasi yang lebih konkret masih terbatas. Misalnya, tantangan terkait ketimpangan aksesibilitas dan efisiensi logistik antar wilayah kurang dieksplorasi lebih jauh. Selain itu, meskipun konsep ekosistem pelabuhan diperkenalkan, interaksi antar aktor dalam ekosistem tersebut dapat diuraikan lebih detail untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Terkait paparan pengelolaan pelabuhan oleh pemangku kepentingan yang tumpang tindih, menurut saya pemaparannya terlalu singkat dan kurang menggambarkan kondisi dengan begitu jelas.
Komparasi dengan Artikel Sejenis
Jika dibandingkan dengan jurnal transportasi laut oleh Sujarwanto. S yang berjudul “Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhan di Indonesia”, bab buku ini memberikan konteks yang lebih luas dan pemahaman konseptual, sementara jurnal memberikan analisis yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik. Jurnal tersebut cenderung menyajikan analisis masalah dan solusi yang lebih mendalam, didukung oleh metodologi penelitian yang lebih terstruktur, sementara bab buku memberikan tinjauan yang lebih luas namun dengan kedalaman analisis yang mungkin tidak sedalam jurnal. Terakhir, bab buku ini sepertinya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca umum, sementara jurnal tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik.
Kesimpulan dan Saran
Secara keseluruhan, bab ini telah memberikan kontribusi dalam memahami sistem dan tata kelola kepelabuhanan di Indonesia. Penulis berhasil menyajikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelabuhan. Bab ini sangat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu logistik dan transportasi. Sebagai masukan, penulis dapat menambahkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai solusi konkret untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Misalnya, pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi pelabuhan atau strategi untuk meningkatkan konektivitas antar pelabuhan di wilayah yang berbeda. Dengan demikian, bab ini akan menjadi sumber informasi yang lebih lengkap dan relevan dalam pengembangan kepelabuhanan di Indonesia.
Referensi
Sujarwanto, S. 2020. Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhan di Indonesia. Jurnal Penelitian Transportasi Laut,. Jakarta. Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Badan Litbang Perhubungan. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/339910599_Peningkatan_Sistim_Manajemen_Kepe labuhanan_di_Indonesia/fulltext/5e6b8027a6fdccf321d993b1/Peningkatan-Sistim-Manajeme n-Kepelabuhanan-di-Indonesia.pdf
Jaya, W. H. & Purwoto, H. 2024. “Telaah Sistem dan Tata Kelola Kepelabuhan di Indonesia Serta Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Pelabuhan Komersial”, dalam S., Gurning R. O. S., & Parikesit, D. (Eds.). Seri Buku Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia: Perspektif Kebijakan Pengembangan Pelabuhan di Indonesia (hlm. 67-103). Jakarta: PEnerbit Buku Kompas.
Critical Review ini dibuat oleh Donnie Trisfian untuk diikutkan sebagai entri dalam lomba Critical Review Buku Seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).